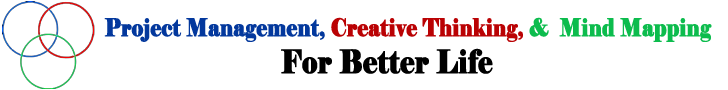Resensi
Monday, January 20, 2014
Sastra Indonesia Bangkit bersama Tenggelamnya Van der Wijck
Saya belum lahir ketika itu, September 1962, ketika sastrawan Pramoedia Ananta Toer pertama kali mengait-ngaitkan novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, karya Buya Hamka (1938), dengan novel Sous les Tilleuls, karya Jean-Baptiste Alphonse Karr (1832) dalam versi bahasa Arabnya hasil terjemahan Mustafa Lutfi al-Manfaluti. Konon kabarnya, isu itu kemudian menjadi polemik yang seru di kalangan para ahli.
Yang saya tahu kemudian adalah isu plagiasi yang dihembuskan oleh segelintir sastrawan anggota Lekra yang berafiliasi dengan komunis di masa itu tidak bertahan lama. Provokasi mereka tidak sanggup menangkis argumentasi pembelaan dari begawan sastrawan hebat Indonesia sekelas H.B. Jasin, A Teew, dll. Mungkin inilah yang dikatakan pepatah lama, anjing menggonggong kafilah berlalu.
Fakta yang terjadi setelah itu, alih-alih lenyap dari peredaran, roman karya ulama besar Indonesia itu justru terus bergulir tanpa bisa dibendung memasuki relung hati anak bangsa ini dan menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Karya ini terukir sebagai karya monumental dalam sejarah sastra Indonesia menembus dimensi waktu.
Karya yang dianggap karya terbaik Buya Hamka dalam bidang fiksi itu menandai bangkitnya sastra Indonesia. Sastra Indonesia justru menggeliat bangkit bersama kisah tenggelamnya sebuah kapal Belanda yang benamaVan Der Wijck dalam perjalanan dari Surabaya ke Batavia (Jakarta).
Lama sekali bentangan waktu antara pertama kali saya mengenal nama Zainuddin dan Hayati, dua tokoh sentral cerita ini yang dideskripsikan melalui kalimat-kalimat oleh Buya Hamka, sampai dengan kemunculan mereka dalam bentuk sosok yang bergerak di layar lebar.
Rasanya, ketika itu saya masih di SMP, tahun 1975-1977, dan belum tahu lagi apa itu sastra dan apa itu bukan sastra, ketika guru bahasa Indonesia memperkenalkan novel itu kepada kami paragraf demi paragraf. Saat itu kami hanya belajar untuk mengenal apa itu plot, karakter, dan setting di dalam sebuah karya fiksi, dengan mengambil tugas membahas karya pujangga itu.
Kini, di tahun 2014 ini, tepatnya Ahad malam Senin, 19 Januari 2014, saya baru merasakan denyut getaran adegan demi adegan dalam novel klasik ini dalam bentuk karya film dengan judul yang sama, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Film ini membongkar kembali memori saya yang telah hilang tentang jalan ceritanya, lebih-lebih nama karakternya.
Satu kata penting dari saya tentang film ini: HEBAT.
Sunil Soraya, sang sutradara, dengan seluruh anggota timnya yang pasti tidak sedikit, tidak bekerja sia-sia. Hasil kerja keras yang konon kabarnya memakan waktu tidak kurang 5 tahun dan menelan biaya yang tidak sedikit itu akhirnya mampu memukau penonton Indonesia seperti saya untuk duduk selama kurang lebih 3 jam, tegang. Durasi selama itu ternyata tidak membuat pinggang saya pegal.
Sejak awal, Zainuddin (diperankan Herjunot Ali) bermain sangat pas dengan pasangannya Hayati (diperankan Pevita Pearse) di film ini. Keduanya, bersama tokoh lain: Azis (diperankan Rahadian) dan Muluk ( Randy Danistha), berhasil mengaduk-aduk emosi.
Saya menyesal telah menganggap remeh nasihat teman yang sedang terbaring di Rumah Sakit Pertamina karena gejala stroke yang dideritanya. Ketika saya menjenguknya, dia menasihati saya agar membawa handuk kecil kalau mau menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck itu.
“Handuk?”
“Ya, untuk mengelap air mata,” katanya serius.
Film dengan plot kisah cinta di alam Minangkabau bernuansa waktu 1930-an itu benar-benar mengalirkan air mata saya berburai membasahi pipi. Malu juga rasanya kalau penonton sebelah tahu saya duduk berguncang ketika harus mengubur haru di dada. Kisah cinta Zainuddin dan Hayati adalah kisah cinta berbalut adat, agama, dan nafsu. Walaupun ada ilmu, manusia ternyata tetap tidak sempurna: terkadang dendam, terkadang iba. Sakit dan mati adalah bayaran yang selalu diminta oleh cinta karena manusia memang makhluk yang lemah tidak berdaya.
“Pisang tak akan berbuah dua kali,” jawab Zainuddin dengan dendam membara ketika Hayati menyatakan permohonan maafnya setelah kekasihnya itu sadar kalau ia terlanjur berkhianat dan terlanjur mengukur cinta dengan kemiskinan. Cinta tapi takut melarat adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Manusia juga, jika seorang sahabat yang di suatu ketika tidak peduli agama, justru tiba-tiba datang menghembuskan asma Tuhan di lubuk hati yang sedang gelisah sedangkan yang berilmu agama tidak mampu melawan nafsunya sendiri.
Kisah Tenggelamnya Kapal Van der Wicjk yang telah diedarkan sejak 76 tahun yang lalu namun baru diluncurkan sebagai film di pertengahan Desember 2013 tahun lalu itu bercerita tentang drama manusia, lengkap dengan karakter-karakternya yang saling berlawanan arah.
Alur kisah yang runut namun klimaksnya tidak tunggal (tidak seperti kebanyakan cerita) berhasil ditata oleh sang penulis skenario film ini menjadi sebuah plot dengan konflikasi yang apik dalam bentuk multi climax. Klimaks-klimaks kecil di akhir setiap episodenya berhasil disusun membangun klimaks yang lebih besar sebelum akhirnya ketragisan ending-nya (kematian Hayati) terkeskplorasi sempurna. Ini bukan kerja mudah. Siapapun yang pernah mencoba menulis novel, apalagi kemudian memindahkannya menjadi skenario film, pasti galau ketika berhadapan dengan situasi ini. Tidak aneh kalau penulisan skenario film ini kabarnya direvisi berkali-kali sehingga memakan waktu dua tahun sampai rampung.
Kisah tragis Pendeka Sutan (ayah Zainuddin) yang ada di bagian awal novel yang membunuh pamannya di Batipuh dan membuatnya terbuang ke Jawa, kemudian ke Makassar, sama sekali tidak disentuh dalam film ini. Ini mungkin disengaja karena kisah yang akan diangkat harus langsung tertuju kepada tokoh utama. Tim sinematografi ini cukup cerdas karena latar belakang ayah Zainuddin langsung terinformaasikan kepada penonton melalui suara Mak Base, pengasuh Zainuddin waktu kecil, bersamaan dengan ketibaan Zainuddin di rumah keluarga ayahnya di Batipuh, Padang.
Terus terang, Tragedi seperti Romeo & Juliet karya William Shakespare belum seberapa hebat dibandingkan dengan tragedi Zainuddin dan Hayati ini.
Adegan yang layak mendapat acungan jempol saya dalam film ini adalah adegan ketika Hayati mengucapkan sumpah sehidup semati kepada Zainuddin di pinggir sungai dengan setting hutan. Dengan pepatah-petitih khas Minangkabau, Pevita Pearce pandai sekali mengatur sorot matanya yang tajam ke arah Herjunot Ali melukiskan bagaimana seorang gadis lugu harus menahan malu berjanji di hadapan seorang lelaki kekasihnya. Herjunot Ali yang memainkan peran Zainuddin berlogat Bugis pandai pula menampakkan hatinya yang luluh oleh gadis Minang yang lembut yang bernama Hayati itu. Orang seperti saya yang pernah mendalami seni peran walaupun sebentar tahu bahwa betapa tidak mudahnya memelintir lima emosi: sedih, benci, cinta, harap, cemas, dalam satu adonan akting.
Adegan lain yang saya suka adalah adegan ketika Reza Rahadian (memerankan Azis) ketika menitipkan Hayati kepada Zainuddin. Reza yang pernah bermain hebat sebagai Habibi pada kisah Habibi dan Ainun berhasil menampakkan bahwa sesungguhnya Azis yang arogan itu juga seseorang yang lemah juga, di dalam keputusasaannya, ketika menitipkan Hayati kepada Zainuddin.
Kalau saya boleh berterus terang tentang momen yang membuat airmata saya mengalir sampai ke dagu dan teringat dengan handuk kecil yang tidak saya bawa itu adalah momen ketika Hayati terkejut, kemudian jatuh tersimpuh dengan bibir yang bergetar dan mata terbelalak, melihat lukisan wajahnya terpampang di ruang kerja Zainuddin setelah Muluk (diperankan Randy Danistha) menarik kain penutupnya. Itu adegan bagus sekali.
Sayangnya, Randy Danistha yang bagus di adegan itu kurang ekspresif di adegan lain yang menurut sasya sangat penting, yaitu ketika ajal Hayati sudah dekat, di rumah sakit tempat penumpang kapal Van der Wijck yang naas itu dievakuasi. Mungkin, sutradara sengaja membuat aktingnya seperti itu agar fokus penonton kepada Zainuddin dan Hayati tidak pecah.
Tapi, sebenarnya, kalau ekspresi Randy yang memerankan tokoh Muluk itu dipoles sedikit ketika itu, sehingga sejalan dengan ekpresi Zainuddin, maka saat-saat Zainuddin membacakan talqin di telinga Hayati kemudian menciumi wajah dan bibir Hayati yang telah menjadi mayit itu, akan menjadi saat-saat yang paling memilukan. Artinya, adegan yang sepertinya disiapkan sebagai klimaks ultimum itu betul-betul ultimum.
Musik latar, gabungan kolosal, romantis, dan abstrak yang dihadirkan oleh Nidji di setiap momen-momen dramatis film ini tidak boleh dianggap kecil. Justru, emosi puncak penonton ketika melihat ratap tangis menjadi begitu menyayat hati karena permainan musik latar ini. Begitu cerdasnya, suara manusia yang sedang berteriak histeris justru dihilangkan dan digantikan dengan suara musik yang menegakkan bulu roma.
Hampir-hampir saja saya meninggalkan kantong plastik yang berisi buku yang baru saja dibeli di bawah jok kursi Sinema 21 itu ketika film itu usai, jika penonton yang duduk di sebelah tidak mengingatkan saya. Film usai dengan sebuah resolusi khas semua kisah-kisah tragedi umumnya. Ketika film itu usai, saya pun tidak peduli lagi dengan isu plagiasi, saduran, kiai cabul, atau istilah lain yang dilemparkan oleh sastrawan yang cemburu kepada Buya HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) dengan karya hebatnya ini.
Entah mengapa, saya tiba-tiba menjadi begitu optimis kalau penulis novel dan sineas berbakat Indonesia akan bermunculan satu persatu setelah ini, setelah hadirnya karya sastra klasik Indonesia ini di pentas sinematografi. Mereka akan tahu kalau karya-karya indah percintaan atau romantisme versi Indonesia bisa juga tampil tanpa harus mengumbar nafsu bila serius menggarapnya.
Tontonlah, untuk bagi yang belum menonton. Jangan lupa membawa handuk kecil, ya.