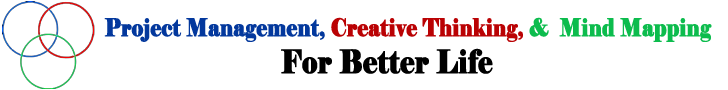Fiksi
Saturday, November 09, 2013
Ketika Eksistensi Jadi Taruhan
"Aku
sama sekali tidak benci pada Micky. Aku hanya marah karena setiap ia menengok
adik-adiknya, ia selalu meludahi mereka,"
bisik hati Kimmy mengenangkan mengapa ia sering menampar wajah anak
lelakinya itu.
"Padahal mereka
itu kan adik-adik yang seharusnya disayangi oleh setiap kakak."
Sore
ini, sudah tiga hari Micky tidak pulang ke rumah. Suasana sore yang
biasanya riuh oleh suara Micky menyapa siapa saja yang datang, kini sepi dan
hening. Hanya tetesan hujan gerimis yang menusuk-nusuk atap berbunyi
nyaring. Tidak ada tanda-tanda Micky akan pulang. Sejauh apapun ia
bermain, ia pasti sudah ada di sini di waktu dan suasana seperti sekarang.
Kimmy
duduk menerawang. Perenungan filosofis yang dalam sedang menghampiri dirinya.
Yang ada padanya sekarang hanyalah sebuah fakta. Yang ada di balik fakta itu
hanya misteri, atau kegelapan, atau teka-teki, atau apa saja nama yang lebih
sesuai untuk sesuatu yang tak jelas hakikatnya. Sambil membiarkan hatinya
melompati semua simbol-simbol yang tak mudah dibaca, mata Kimmy sayu menatap
langit yang gelap yang ditutupi gumpalan awan yang hitam. Mungkin ia sedang
mencari suatu jawaban dari matahari sore
yang tidak menyembul walau seujung jari.
Dadanya kian gemuruh. Sebagai makhluk yang berperasaan, ia khawatir akan
sesuatu yang buruk terjadi pada Micky.
Harga
diri memang segala-galanya bagi siapapun. Kalau bukan karena harga diri, tidak
akan ada perang, protes, demonstrasi, gugat-menggugat di dunia ini. Bagi Micky, mungkin tamparan
seorang ibu bukan berarti penghinaan apalagi kriminalitas. Ibu menampar anak
yang nakal tentu biasa. Tapi, tamparan ibu bisa berarti penolakan ekistensinya
sebagai anak. Apalagi Kimmy menampar Micky sambil meladeni kemanjaan adik-adik
Micky. Ini mungkin masalah harga diri bagi Micky. Lari memang sering dipilih
oleh siapapun yang tak bisa menemukan eksitensinya di dalam sebuah keluarga
atau komunitas. Bahkan ada yang memilih bunuh diri.
Tanpa
tahu darimana jawaban itu berasal, intuisi Kimmy bergerak menuju jawaban bahwa
Micky pasti lari. Ia ingin menemukan eksistensinya di tempat lain dengan memilih lari. Ini
pilihan yang paling wajar.
"Tapi,
apakah ia benar-benar lari?" bisik Kimmy mendebat hatinya sendiri.
"Bukankah ia terlalu kecil untuk lari? Lari kemanakah ia? Lari memerlukan
tempat berlindung yang baru."
Bercampur
rasa sesal, hati Kimmy menjadi bertambah
galau tak menentu. Pilihan-pilihan baru mucul secara tiba-tiba. Suara-suara baru menyuarakan alternatif yang
tidak boleh dianggap enteng.
"Jangan-jangan
ia mati tenggelam dihanyutkan oleh air yang bergulung-gulung. "
Ini
sangat logis. Musim hujan yang mengguyur Jakarta di bulan ini tidak hanya mampu
menenggelamkan makhluk hidup tapi bahkan mampu menggusur gunung.
"Atau
ia digilas kereta api ketika menyeberang tidak hati-hati."
Ini juga
tak kalah logis. Perlintasan kereta api di Jakarta telah menelan banyak nyawa
sejak beberapa dekade terakhir.
"
Atau ia diculik orang yang tak mengenal belas kasihan."
Setiap
ia biarkan suara-suara itu menghunyamkan alternatif, semakin dadanya terasa
menyempit. Ia tahu kalau alternatif jawaban tidak boleh dibunuh begitu saja.
Semua alternatif mesti dikembangkan. Itulah logika. Siapa tahu, jawaban yang
sesungguhnya ada pada salah satu alternatif yang dikira aneh. Tapi, bila
dibiarkan, alternatif-alternatif itu akan saling kait mengait dan tumbuh
seperti kanker ganas di hati. Akhirnya seperti benang kusut.
Di sore
yang sesunyi ini, Kimmy tak bisa menahan air mata yang telah mendanau di balik
kelopak matanya. Fitrahnya sebagai ibu yang telah melahirkan Micky tidak bisa
digusur begitu saja oleh pertanyaan-pertanyaan filosofis. Betapapun ada banyak kemungkinan yang
ditawarkan pikirannya, yang diharapkan oleh perasaannya adalah bahwa Mikcy
lari.
Mengapa
ia berharap Micky lari? Lari masih menyisakan harapan. Pilihan lain betapapun
logis, tidak memberi peluang. Ia benci dengan sesuatu yang tidak menawarkan
apa-apa. Ia benci dengan sesuatu yang hanya menjanjikan kepasrahan.
Pikiran
dan perasaan memang sering tidak sejalan. Matanya yang sayu itu
secara pelan meneteskan air mata yang tak terendung lagi. Air mata itu kemudian
mengalir secara pelan membasahi pipinya dan menutupi rongga hidungnya. Air
mukanya memilih berpihak pada perasaan bukan pada pikiran.
"Jika
engkau pulang, aku akan memelukmu dan tak akan menampar-namparmu lagi,"
janji Kimmy kepada bayangan wajah Micky yang tiba-tiba muncul di hadapannya
sambil ia mengapitkan kedua bibirnya yang bergetar menahankan ledakan gemuruh
di dada.
Adik-adik
Micky yang ikut menemani Kimmy tak bisa menyembunyikan kesedihan melihat ibu
mereka yang bermuram durja itu, dalam kesepian, betapapun mereka tetap mencoba
mengalihkan perhatian Kimmy dengan canda-canda yang mereka buat.
Kimmy
pun mengulurkan lidahnya menjilati bulu keempat anaknya yang masih kecil-kecil
itu satu persatu. Semua anak kucing itu tiba-tiba mendekap ibunya ketika
terdengar suara petir menggelegar. Di dalam kehangatan bulu Kimmy yang tebal
itu, di tengah suara hujan bercampur suara angin yang tiba-tiba keras,
anak-anak Kimmy itu dengan jelas mendengar Kimmy berbisik di depan telinga
mereka dengan lirih, "I love you my children."
Sambil
cekikikan mereka berseru," I love you, Mom."